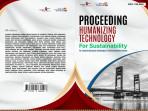Berita Adv
Upaya Pelestarian Kebudayaan : Tampaknya, Kita Harus Belajar dari Mereka
Usaha ini mereka lakukan tanpa sama sekali berhubungan dengan pengetahuan budaya (culture knowledge).
Yudhy Syarofie, Budayawan Sumsel
Usaha pelestarian kebudayaan yang saat ini semakin keras dengungnya tampak sebagai sebuah usaha yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, memberi napas segar bagi pelestarian cagar budaya.
Ada ruang-ruang bagi usaha pemanfaatan benda, bangunan, atau kawasan cagar budaya, yang tidak diakomodasi pada UU sebelumnya.
Napas segar ini kian terasa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Adanya UU ini seolah menjadi jaminan bagi semua warga negara (yang peduli) untuk melestarikan, merevitalisasi, dan memanfaatkan tinggalan-tinggalan budaya benda itu.
Pemerintah, mulai tingkat kabupaten/kota hingga nasional pun membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bersifat independen.
Kepala daerah –sesuai tingkatannya—pun dapat menetapkan objek diduga cagar budaya (ODCB) sebagai cagar budaya sesuai rekomendasi TACB.
Kesadaran akan pentingnya objek cagar budaya ini pun menjadi sesuatu yang lumrah di semua instansi.
Misalnya, Kodam II Sriwijaya mengajukan surat permintaan peninjauan kecagarbudayaan atas rencana lembaga itu merenovasi RS AK Gani.
Begitupun Balai Besar Jalan dan Jembatan yang memiliki program pemasangan lift untuk memfungsikan menara Jembatan Ampera sebagai fasilitas wisata.
Lantas, di mana posisi masyarakat (umum) pada situasi ini?
Kisah Nurjanah
Ada dua pengalaman saya yang berhubungan dengan upaya pelindungan dan pelestarian budaya itu.
Usaha ini mereka lakukan tanpa sama sekali berhubungan dengan pengetahuan budaya (culture knowledge).
Usaha itu pun sampai mengorbankan sebagian “pendapatan”.
Pertama, saya berjumpa dengan Nurjanah, yang kusapa sebagai Mbah Jana di Desa Samirejo, Mariana, Kabupaten Banyuasin, pada tahun 2010.
Ini kali kedua saya bertemu dengannya.
Lima belas tahun sebelumnya, saya berjumpa dengannya saat terjadi penemuan keping perahu yang diduga berasal dari masa Sriwijaya.
Perempuan --saat itu diperkirakan berusia 70-an tahun-- itu sangat senang dengan pertemuan kedua kami.
Beliau pun saat menceritakan perbincangan dengan “Pak Mingun”, maksudnya, Yves Manguin, ahli arkeologi maritim dari EFEO (Lembaga Penelitian Perancis Untuk Timur Jauh).
Saat itu, EFEO melakukan penelitian atas sisa-sisa perahu kuno dari masa 610-775 Masehi. Pertanggalan itu diperoleh dari uji karbon (C-14) atas sembilan papan kayu dan sebuah kemudi sepanjang 23 meter.
Dari rekonstruksi Manguin inilah, diperoleh fakta bahwa teknologi kapal itu berbeda dengan teknologi perahu kuno model Cina.
Apabila teknologi Cina menggunakan bilah-bilah kayu untuk mengencangkan bagian lambung serta paku (bahan besi) untuk menguatkan kerangka dan dinding penyekat, teknologi perahu di Samirejo ini sangat berbeda.
Menurut Manguin, teknologi yang digunakan pada perahu Samirejo adalah teknik papan-ikat dan kupingan-pengikat (sewn plank and lashed-lug technique).
Teknik rancang bangun perahu seperti ini, menurut Manguin, hanya berkembang di perairan Asia Tenggara.
Tonjolan segi empat (tambuku) digunakan untuk mengikat papan-papan dengan gading-gading.
Pengikatnya berupa tali ijuk yang dimasukkan pada lubang di tambuku.
Untuk memperkuat ikatan tali ijuk, digunakan pasak kayu.
Teknik pembuatan perahu jenis ini diperkirakan sudah ada sejak masa awal Masehi.
Bukti tertua penggunaan teknik ini dijumpai pada sisa perahu kuno di situs Kuala Pontian di Tanah Semenanjung, yang berasal dari abad III-V Masehi.
Dengan demikian, ini merupakan salah satu bukti lagi –di samping prasasti-prasasti, juga sisa kapal di Karanganyar, Kolam Pinisi, serta beberapa bentuk serpihan kapal di beberapa daerah lain di wilayah Sumsel—untuk keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang.
“Puing” papan, yang panjangnya mencapai 7 meter berikut serpihan tali ijuk (Arrenga pinnata) itu ditemukan terkubur di lebak ini.
Untuk memeliharanya agar tak rusak, tim arkeologi kemudian memutuskan untuk kembali memendamnya di tempat yang sama.
Di tempat ini pula, pernah ditemukan mangkuk keramik dan tempayan dari Dinasti Yuan (1279-1368), pecahan manik-manik, pecahan bahan kaca, bahkan emas.
Karena kepingan papan perahu itu dibenamkan di lahan kebunnya, Nurjanah memutuskan untuk tidak lagi menanam padi atau sayuran di lahan itu.
Dia mengaku tidak berani mencangkul di tanah itu, takut merusak kepingan papan yang tertanam.
Lalu, apakah dia dibayar?
Menurutnya, pernah sekali dibayar.
Berapa honornya? Rp400 ribu.
Jamasan
Saya juga bertemu dengan Sunyoto di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas.
Sunyoto adalah Ketua Turonggo Jati, grup kuda kepang. Sunyoto juga merupakan warga keturunan transmigrasi ABRI tahun 1971.
Seluruh keturunan transmigran merupakan etnis Jawa yang heterogen dalam beragama; yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu.
Perkumpulan Seni Jaranan Turonggo Jati ini menghimpun semua pemeluk agama itu.
Di samping kelompok ini, ada pula anggota sanggar yang berasal dari etnis Rawas, Minang, Bugis, dan Bali.
Setiap tahun, dengan para tokoh Turonggo Jati sebagai pelaksana utama, yaitu pada 1 Muharram atau 1 Suro, diadakan Sedekah Bumi, yaitu selamatan desa.
Pada saat inilah, lima agama yang dianut warga diperlakukan sama.
Pada saat sedekah bumi ini, dilakukan jamasan, yaitu pemandian benda pusaka milik siapa pun.
Sebagai pemimpin komunitas, jamasan dilakukan oleh Sunyoto.
Beragam pusaka terkumpul di sini.
Sebagian besar keris merujuk ke Mataram.
Menurut Sunyoto, keris dan pusaka lainnya itu umumnya merupakan bawaan dan pegangan kakek atau bapak mereka yang datang ke daerah ini sebagai transmigran.
Di samping itu, mereka juga membangun candi (untuk umat Hindu) di tempat itu.
Saat penggalian, beragam benda kuno ditemukan.
Temuan ini pun dikumpulkan di satu tempat, dan tidak ada di antara mereka yang mengganggunya.
Dalam perbincangan saya dengan beberapa arkeolog pelestari, proses yang berlaku pada jamasan itu, disadari atau tidak, adalah usaha pelestarian.
Bila keris yang dilumuri dengan air jeruk purut berfungsi membersihkan kotoran yang menjadi cikal bakal karat, demikian pula perabunan –pada jamasan menggunakan kemenyan—dapat membuat keris yang berbahan logam selalu terjaga kondisinya.
Lantas, bagaimana Sunyoto dan warga yang biasa bersamanya mengurusi hal ini?
Mereka tetap saja dengan kesehariannya; berkebun, berdagang, kerja PNS, dan bermain jaran kepang.
Kisah Nurjanah dan Sunyoto merupakan dua wajah pelestari warisan budaya yang hadir secara nyata di tengah-tengah kita.
Disadari atau tidak, masyarakat di akar rumput masih melakukan langkah pelestarian dengan segala keterbatasan.
Mereka berupaya sebisa mungkin agar warisan budaya tetap lestari guna diwariskan pada anak cucu.
Bagaimana dengan kita? (ADV)
Berita ADV
Pelestarian Kebudayaan
Yudhy Syarofie Budayawan Sumsel
Yudhy Syarofie
Budaya Sumsel
Tribunsumsel.com
| Astra Motor Sumsel Satukan Kebersamaan Komunitas Honda di Hari Pelanggan Nasional 2025 |

|
|---|
| TAMANSARI SWARNA RESIDENCE by WIKA Realty Luncurkan Cluster Baru dengan Design Lebih Mewah |

|
|---|
| Sambut Libur Akhir Tahun, Novotel Palembang Hadirkan Family Fun and Dine |

|
|---|
| Dosen Gizi UNSRI Dampingi Pesantren Al-Amalul Khair Tingkatkan Kesehatan Mental dan Gizi Santri |

|
|---|
| Komunitas Skutik Premium Meriahkan City Rolling, FDR Luncurkan Ban Ultimate Gen-2 |

|
|---|